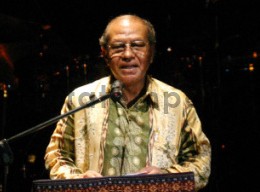Sosok – kelirbali.com
Ngurah Teguh S.Fil-alumni UNHI. Saat menempuh kuliah semester 5, saya disibukkan dengan berbagai huru-hara pikiran, salah satu yang paling menyiksa tapi sekaligus mengasyikkan adalah perkara keilmuan yang saya pelajari. Saya tidak perlu membeberkan soal itu, tapi pada intinya situasi tersebut membuat saya kian involutif melihat dunia, saya pun tidak mampu lagi membedakan mana fiksi dan fakta.
Seorang kawan semasa kuliah (tak perlu saya sebut nama) menawarkan saya untuk bekerja freelance di sebuah studio radio. Katanya, saya akan belajar berbicara lebih lugas, percaya diri, dan lebih retoris, dia yakin hal itu adalah alat penting untuk perkara keilmuan saya. Dengan memikirkan matang-matang saya pun memutuskan melamar menjadi penyiar radio!
Respon pertama kawan-kawan saya adalah heran, kenapa saya mesti memilih dunia broadcasting, kenapa saya mesti memilih ‘dunia pop’ sebagai selingkuhan untuk bidang ilmu yang dipelajari. Ariel Heryanto sudah wanti-wanti bahwa ‘budaya pop’ bisa muncul sebagai sebuah medan produksi dan pertarungan identitas, dan opini yang kemudian bermuara pada pasar. Waktu itu saya hanya berikrar untuk tidak berlama-lama, karena yang perlu saya pelajari hanyalah mempertajam keterampilan untuk berbicara, berargumentasi di depan umum, dan melatih kemampuan retorika (salah satu matkul di bangku kuliah).
Apa yang kemudian saya alami selama beberapa tahun menjadi penyiar tidak persis sama dengan asumsi awal saya. Radio yang diasumsikan sebagai ‘show room’ budaya populer juga telah berubah. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin canggih, akses terhadap informasi begitu mudah didapatkan melalui media sosial, platform digital dan seterusnya. Radio tidak lagi menjadi satu-satunya pusat seseorang untuk mendapatkan informasi aktual atau menunggu kabar terbaru untuk berita bencana atau politik. Jauh dari semua framing itu, ada semacam cultural shift bahwa radio lebih berfungsi sebagai alat untuk meramaikan situasi, atau semacam soundscape bagi mereka yang lagi jenuh, atau kesepian di tengah mobil.
Agaknya, tidak ada yang sepenuhnya benar-benar peduli pada apa yang di-omongin penyiar di radio, kecuali jika ada kata-kata kasar atau kata-kata yang melecehkan SARA. Itulah mengapa dialog interaktif di radio sudah sangat jarang dijumpai, disamping memang tidak efektif karena akses terhadap pengetahuan bisa diperoleh dengan lengkap lewat teknologi digital, pun dialog interaktif di radio sangat dibatasi oleh waktu. Dialog interaktif di radio kemudian berganti menjadi aktivitas tukar-tukar salam bagi mereka yang sudah berusia lanjut, atau setengah abad, sisa-sisa generasi yang masih merindukan kejayaan radio di masa silam. Sisanya lagi adalah pendengar pasif yang hanya sekedar ingin memperoleh keributan dari suara penyiar dan lagu-lagu yang diputar.
Sebagai artefak kebudayaan yang sayup-sayup melihat sinar dan nyala hari kiamatnya, radio kemudian menjadi pertemuan lintas para medioker, kebanyakan dari mereka ini ibu-ibu rumah tangga yang sibuk mengurus anak dan begitu pentingnya keriuhan radio bagi mereka dikala menyetrika baju, para pekerja kasar di suatu pabrik kayu, atau warung lalapan pinggir sawah, atau memang orang-orang iseng yang mencoba mengirim salam sapa dan menelfon dengan nada aneh di malam hari. Dengan demikian, radio menjadi ruang gema bagi mereka yang masih setia menjadi penghayat radio, dan para penyiarnya. Seringkali terjadi hubungan intens antara penyiar dan pendengar atau pendengar radio satu dengan radio yang lain, namun jumlahnya bisa dihitung jari, dan umurnya sudah bisa ditebak.
Namun dibalik segudang perubahan itu, radio menjadi salah satu media yang paling murah untuk diakses dan dinikmati oleh masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah. Kedekatan radio dengan acara-acara kecil-kecilan di masyarakat seperti lomba mancing antar desa, promosi produk-produk kopi lokal, dan seterusnya menandakan radio memang menjadi ruang bagi suatu masyarakat dengan kelas ekonomi tertentu. Maka bagi perusahaan-perusahaan atau korporasi sangat mengerti betul bahwa radio ini masih memiliki fungsi atau memiliki market demand. Ini menandakan, meskipun radio merupakan artefak kebudayaan lisan non visual yang masih tersisa, radio tetap diminati, justru oleh kalangan medioker dan kelas pekerja, khususnya kelas pekerja kasar. Ini adalah poin paling krusial. Justru di tengah kondisi seperti itu, betapa bersyukurnya saya bisa menjadi bagian dari lanskap kultural mereka, meskipun hanya dalam pertemuan virtual di udara, hal tersebut membuat saya menyadari betapa banyak ruang hidup di luar mic dan studio 4×5 meter yang sudah saya ramaikan aktivitasnya. Untuk itu tantangan bagi para penyiar radio kini adalah sebagai media partisipatoris dan orang ketiga yang memediasi hiruk pikuk dunia kontemporer. Tidak hanya melulu sebagai wahana budaya populer.
Doa saya untuk semua penyiar radio tanah air.(den)